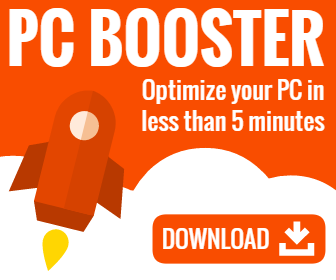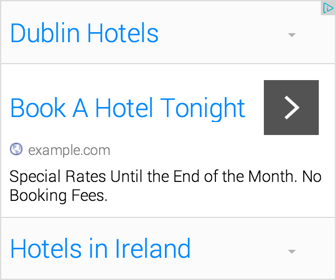JAKARTA, lintasbarometer.com
Tiga hari setelah pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kali kedua, Joko Widodo mengumumkan nama-nama menterinya kepada publik. Setiap partai koalisi yang duduk di parlemen mendapatkan posisi menteri. Bukan hanya koalisi, oposisi pun mendapat kursi menteri, bahkan lebih banyak dari partai koalisinya sendiri.
Partai oposisi yang diakomodasi adalah Gerindra yang dipimpin Ketua Umum Prabowo Subianto, saingan Jokowi dalam pilpres 2014 dan 2019. Dari 43 persen menteri yang berasal dari partai politik, Jokowi mengambil Edhy Prabowo (Wakil Ketua Umum Gerindra) sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dan Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan.
Selain mengakomodasi Gerindra, Jokowi memilih tak memberikan jatah menteri kepada partai-partai pendukungnya di Pilpres 2019 yang tidak mendapat kursi DPR. Tidak ada menteri dari Perindo, PSI, PKPI, dan Hanura.
Gerindra menguasai kursi parlemen sebanyak 78 kursi atau 13,56 persen dari 575 kursi DPR. Jatah menteri yang didapat Gerindra lebih banyak dari PPP yang menjadi pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.
Antisipasi Jokowi
Gerindra memang punya perolehan suara nasional dan kursi parlemen lebih banyak dari PPP. Keputusan Jokowi merangkul Gerindra bisa dibaca sebagai langkah antisipasi apabila kelak ada partai koalisi yang tidak solid. Jika dilihat dari track record selama 20 tahun terakhir, partai yang cenderung rawan mbalelo adalah Golkar. Bahkan Nasdem, yang selama ini loyal mendukung Jokowi, pun punya potensi pecah kongsi mengingat betapa tidak akurnya Surya Paloh dengan Megawati Soekarnoputri.
Dengan komposisi koalisi di luar Gerindra, partai-partai pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin sebenarnya sudah menguasai lebih dari separuh kursi parlemen. Karena itu jika keputusan nantinya berdasar pengambilan suara terbanyak, kebijakan pemerintahan Jokowi sebenarnya tak akan bisa dibendung oposisi.
Tapi jika satu atau lebih partai koalisi itu ada yang menjadi duri dalam daging, Jokowi harus memperhitungkan langkah lain. Apalagi Jokowi sebenarnya punya impian tidak tersandera dengan kepentingan apapun. Bila kepentingan itu termasuk tekanan dari partai politik, mengundang oposisi adalah sebuah “rencana cadangan” kalau-kalau ada partai koalisi yang membelot atau berbeda pendapat.
“Meskipun sudah mayoritas di parlemen, belum tentu mereka [partai-partai] tidak membelot,” kata Direktur Indonesia Political Review Ujang Komarudin kepada Tirto.
Bergabungnya Gerindra juga disambut hangat oleh PDIP, partai pengusung utama Jokowi. Mereka mengakui, masuknya Gerindra adalah untuk memuluskan pemerintahan kedua mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
“Kuatnya pemerintahan, tentunya berdampak pada stabilitas politik nasional sebagai syarat penting percepatan ‘kerja’ pembangunan ekonomi nasional,” kata Hasto dalam keterangan resmi yang diterima Tirto, Selasa (22/10/2019).
Dalam hal mengantisipasi “kenakalan” partai koalisi, Jokowi barangkali bisa berkaca pada pemerintahan SBY. Di periode keduanya (2009-2014), SBY harus menghadapi anggota-anggota koalisi yang mbalelo.
Belajar dari SBY
Dua mobil dibakar dan tak terhitung berapa banyak yang dirusak. Demonstrasi di Jakarta dan sejumlah daerah lain terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berujung vandalistis. Susilo Bambang Yudhoyono memang menaikan harga BBM dengan alasan jelas: kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun itu tak bisa diterima begitu saja oleh banyak orang.
Bukan hanya dari para demonstran, SBY juga menerima pukulan dari partai pendukungnya sendiri. Ada empat kali kenaikan BBM yang dilakukan SBY, yakni dua kali di tahun 2005, satu kali di tahun 2008, dan satu yang terakhir pada 2013. Setiap kali harga BBM dinaikkan, ada saja partai pengusung SBY-Jusuf Kalla/Boediono yang tidak setuju.
Pada 2005 PPP, PAN, PKS, dan PKB melakukan penolakan. Di tahun 2008 giliran Golkar, PAN, dan PKS yang melakukannya.
Apa yang dilakukan partai koalisi SBY memang menjadi hambatan tersendiri. Pemerintahan SBY bahkan makin terpojok ketika PDIP, partai oposisi terbesar, ikut ambil bagian dalam mempersulit pengambilan keputusan pemerintah.
Mengakali tindakan koalisi yang tak bisa ditebak, SBY-Boediono kemudian membentuk Sekretariat Gabungan (Setgab) setelah Pilpres 2009. Isinya adalah partai-partai pengusung keduanya, yakni Demokrat, PKS, PAN, Golkar, PPP, dan PKB. Ketua Umum Partai Golkar saat itu, Aburizal Bakrie, menjadi pimpinannya. Pada Pileg 2009 Golkar adalah partai yang memperoleh suara terbanyak setelah Demokrat.
SBY mengakui pembentukan Setgab adalah demi memudahkan pengambilan keputusan dalam kabinet bersama dengan parlemen.
“Setgab adalah forum atau fasilitas untuk koordinasi dan konsultasi sesama anggota koalisi. Baik sesama eksekutif maupun legislatif,” kata SBY pada 2010 seperti diberitakan Kompas. “Tujuannya sekali lagi agar pemerintahan yang dibangun oleh koalisi bisa menjalankan tugasnya secara efektif, mekanisme koordinasi dan konsultasi antara anggota koalisi yang ada di DPR dan pemerintah juga berhasil dengan baik.”
Kendati demikian posisi SBY tak juga aman. Pada 2013, saat kenaikan BBM yang terakhir, PKS masih bersikap mbalelo dengan menolak kenaikan tersebut. PKS kala itu punya perolehan kursi parlemen tertinggi keempat. Bersama PDIP yang berada di urutan ketiga, mereka menjadi penghambat pengambilan keputusan antara parlemen dan pemerintah.
Dosen hukum tata negara dari Universitas HKBP Nommensen, Januari Sihotang, menilai partai koalisi SBY-Jusuf Kalla maupun SBY-Boediono bersatu bukan karena kesamaan ideologi, tapi dengan bingkai yang sangat pragmatis.
Akibatnya, partai koalisi bisa berubah sikap dan menyulitkan SBY sendiri. Dalam buku Pemilu dalam Transisi Demokrasi Indonesia (2018), Januari menulis, “Dengan bingkai yang sangat pragmatis tersebut, karakter partai-partai dalam berkoalisi menjadi sangat longgar, tak disiplin, dan oportunis.”
Januari mengatakan pula bahwa sebab lain gagalnya koalisi satu suara adalah kurangnya harmonisasi antara partai politik. Dengan koalisi gemuk, pengambilan keputusan yang seharusnya menjadi mudah malah menjadi kontraproduktif karena banyak kepentingan yang harus diakomodasi.
“Pembentukan koalisi terlalu berorientasi pada kuantitas dibandingkan dengan kualitas,” lanjut Januari. “Harus diakui, inilah salah satu kekeliruan koalisi yang dibangun SBY.”
Itulah yang menjadi PR Jokowi saat ini. Meski ia sudah meminimalisasi upaya pembelotan partai koalisi, caranya merangkul oposisi pun belum tentu memuluskan pemerintahannya.(tirto.id/j)